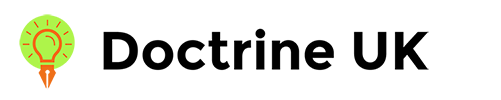Sumber: Julia Volk, pexels.com
ARTICLE
Penulis: Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, Mahasiswa Doktoral bidang Politics and International Studies, University of Leeds
Pandemi COVID-19 telah membuat negara-negara mengalihkan banyak sekali sumber daya untuk menghadapinya, tak terkecuali Indonesia. Gelaran pertemuan para pihak untuk isu lingkungan global, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, UK tahun 2021 juga mengalami penundaan untuk fokus pada pandemi. Hanya setahun berselang, COP27 kembali diselenggarakan di Sharm El-sheikh, Mesir.
Salah satu kesepakatan penting dalam COP26 telah menghasilkan The Global Goals on Adaptation (GGA) sebagai bagian dari Paris Agreement.
GGA merupakan panduan untuk menilai kesiapan dan kapasitas sebuah negara dalam melakukan adaptasi terhadap krisis iklim. Adaptasi yang dimaksud dalam hal ini ialah kemampuan sistem, lembaga, manusia, dan organisme lain untuk menyesuaikan diri terhadap potensi kerusakan, kemampuan mengambil kesempatan, atau menghadapi akibatnya (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2017).
Adaptasi mencakup manusia, lingkungan, beserta seluruh sumber dayanya. Penting melakukan adaptasi ini bukan hanya untuk ketahanan negara, namun juga kelompok-kelompok rentan, baik dari segi kebencanaan maupun kerentanan struktural seperti karena budaya dan gender.
Adaptasi sangat penting bagi Indonesia yang sangat mengandalkan kekayaan alam untuk meningkatkan perekonomiannya. Terlebih lagi, luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan Indonesia harus memiliki sistem yang menyeluruh agar kelompok rentan dapat terlindungi seterusnya. Untuk itu inisiatif dan gerakan di tingkat akar rumput sangat bernilai untuk mencapai kemampuan adaptasi yang sepenuhnya. Saat ini kelompok rentan perubahan iklim di Indonesia seperti masyarakat pesisir, masyarakat adat, dan anak-anak serta kaum wanita di daerah kritis belum banyak mendapat porsi dalam pembahasan adaptasi krisis iklim di Indonesia. Sebagai contoh, karena terjadi abrasi daerah pesisir, banyak penduduk yang kehilangan mata pencahariannya dan terpaksa terlibat prostitusi.
Sebenarnya, tidak ada indikator yang berlaku umum untuk menilainya karena kondisi tiap negara berbeda. Untuk itu, konteks lokal sangat membantu untuk merumuskan indikator dan kemudian untuk membuat kebijakan berbasiskan data. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memiliki Knowledge Centre Perubahan Iklim sebagai pusat pengetahuan untuk merumuskan aksi perubahan iklim, namun tak satu pun terdapat informasi tentang bagaimana KLHK sebagai pengawal bidang krisis iklim ini memasukkan konten lokal dan apakah kondisi lokal sudah menjadi bahan pertimbangan.
Jejaring Cendekiawan dan Perguruan Tinggi
Lembaga perguruan tinggi telah jamak berpartisipasi dalam penyusunan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan naskah akademik lainnya. Sayangnya, sering pula warga kampus dicela sebagai pemberi “stempel” kelayakan operasi perusahaan dan proyek pemerintah dari segi lingkungan. Untuk menjaga marwah akademik dari fenomena demikian, penting untuk menyatukan berbagai pusat studi dan lembaga pengkaji (think tank) terkait lingkungan di Indonesia.
Pada rangkaian ajang pendahulu sebelum pertemuan COP26 Glasgow dimulai, para akademisi di UK membentuk COP Universities Network dan Climate Expo. Peneliti bidang apapun yang merasa risetnya beririsan dengan kepentingan lingkungan dapat bergabung dengan mudah dan terdapat sesi presentasi selama beberapa rangkaian.
Peneliti di Indonesia masih perlu berkolaborasi dan tidak terjebak perangkap linearitas ilmu, karena penelitian tentang iklim sangat interdisipliner. Selain itu dengan berjejaring, para peneliti dapat lebih independen dan berbagi sumber daya, untuk mengangkat tema-tema lokal yang vital.
Tak hanya di dalam negeri, keberadaan kelompok akademisi Indonesia di luar negeri juga sangat diperlukan. Banyak dari riset mereka yang mengangkat kearifan lokal dan terhubung dengan lembaga lingkungan dunia. Jika sumber daya ini disatukan, maka lebih mudah bagi pemerintah untuk menyusun kertas posisi untuk COP di masa akan datang, dan upaya adaptasi pada khususnya.
Komunitas Rentan Harus Diutamakan
Masyarakat sipil memiliki kemampuan adaptasi secara kolektif. Pemerintah Indonesia menerapkan Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai barometer terlaksananya aksi mitigasi dan adaptasi di tingkat lokal. Dengan berbagai manfaat sosial-ekonomi yang diberikan, tentunya dukungan masyarakat dapat lebih berkelanjutan. Namun, kegiatan masyarakat seperti pengolahan sampah, pembangunan taman kecil, dan pembersihan lingkungan seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Banyak proyek adaptasi yang justru berlokasi di daerah yang sudah terbangun sarana dan prasarana, meskipun ada pula yang berlokasi di Papua Barat dan Pulau Sabu, NTT.
Aktivitas dalam Proklim belum menyasar masyarakat yang dalam kondisi paling rentan, sementara mengurangi kerentanan ialah tujuan utama adaptasi. Contoh masyarakat rentan ialah mereka yang bahkan kurang terekspos oleh data pemerintah, misalnya kaum wanita pekerja di kebun kelapa sawit yang tidak masuk dalam daftar pekerja di Dinas Ketenagakerjaan. Demikian pula kelompok penyandang disabilitas yang dinyatakan PBB sebagai kelompok paling rentan dan kurang mendapat keadilan iklim, karena sarana dan peraturan tidak menyoroti mereka.
Kenyataannya, mengacu pada Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim, dana untuk adaptasi masih sangat jauh di bawah mitigasi, dan sangat bergantung pada hibah bilateral dan multilateral.
Desakan untuk pengesahan peraturan adaptasi berbasis lokal
Demi keberlanjutan adaptasi, regulasi dan undang-undang yang membawahinya perlu segera disahkan. Tren menunjukkan bahwa negara-negara di berbagai benua sudah membuat regulasi khusus adaptasi, baik dalam undang-undang tersendiri maupun diselipkan ke regulasi yang telah ada. Bahkan Kazakhstan melakukan keduanya. Namun kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kapasitas untuk mengumpulkan data dan sumber daya, utamanya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Untuk itu diperlukan kolaborasi lebih jauh dengan wilayah yang lebih makmur, serta pemberian mekanisme insentif bagi pembangunan kawasan yang mau membuat peraturan daerah untuk adaptasi. Sebagai contoh, provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara telah berhasil memberlakukannya. Pembuatan rencana adaptasi sudah tepat, namun untuk keberlanjutan tetap dibutuhkan peraturan daerah yang disusun secara partisipatif dan komprehensif.
Penutup
Indonesia sukses menyelenggarakan COP13 tahun 2007 di Bali, dan menghasilkan kesepakatan penting berupa Bali Road Map. Sebagai turunannya, terdapat Bali Action plan yang juga mencakup adaptasi. Sebagai catatan, tidak setiap pertemuan COP bisa menghasilkan kesepakatan yang berarti. Artinya, Indonesia memiliki kekuatan politik dan keahlian teknis yang dipercaya para pihak. Jika Indonesia sebagai rumah keanekaragaman hayati mampu memperlihatkan kinerja adaptasi hingga ke level daerah, posisi Indonesia akan semakin sentral di meja negosiasi COP di masa depan. Untuk itu, kementerian dan lembaga yang berwenang perlu memiliki pandangan strategis jangka panjang untuk aktualisasi adaptasi hingga mencapai para kelompok rentan.
***
*) Materi pada artikel ini memiliki cakupan pembahasan yang lebih sempit dibandingkan materi di dalam salindia terlampir.
**) Artikel ini adalah aset pengetahuan organisasi Doctrine UK dengan nomor registrasi 2022-11-12-Articles.
Lampiran
Presentasi
terlampir adalah materi akademik tanpa telaah formal keilmuan (non-reviewed) yang diedarkan semata-mata untuk memantik komentar dan diskusi. Oleh karena itu: