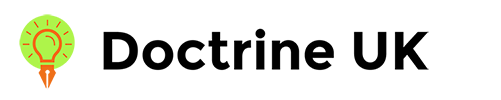Sumber: Rio Lecatompessy, unsplash.com
ARTICLE
Penulis: M. Yorga Permana, Dosen di Sekolah Bisnis dan Manajemen, ITB dan Mahasiswa Doktoral di London School of Economics and Political Science (LSE)
Sudah sejak lama kebijakan kewirausahaan menjadi mantra bagi pembangunan. Bagi para ekonom, wirausaha dipercaya sebagai penggerak inovasi (Schumpeter, 1942) dan sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Acs dan kawan-kawan, 2004). Sementara bagi politisi dan pengambil kebijakan, kebijakan kewirausahaan dengan jargon ‘menciptakan wirausaha sebanyak-banyaknya’ adalah kebijakan populer yang disukai oleh konstituen. Turunan kebijakannya beragam, dari program yang klasik seperti pelatihan, pendampingan, dan akses kepada pasar dan permodalan, hingga program yang relatif modern seperti pengembangan ekosistem wirausaha, inkubator startup, serta digitalisasi bisnis.
Tentu kita bangga dengan Nadiem Makarim (Gojek) dan Achmad Zaky (Bukalapak) sebagai pendiri usaha baru yang kemudian memiliki valuasi yang tinggi dalam waktu singkat. Pertumbuhan wirausaha, khususnya yang bergerak di sektor teknologi digital, terbukti telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal maupun nasional: menciptakan lapangan kerja baru, menaikkan taraf hidup, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Berdasarkan data dari Crunchbase, sejak tahun 2010 saja ada sekitar 500 startup baru di Indonesia yang paling tidak sudah masuk ke tahapan pendanaan seed, mendapatkan pendanaan total lebih dari USD 9,5 milyar, menyerap lebih dari 40 ribu orang tenaga kerja, dan sekitar 10 persen di antaranya sudah diakuisisi atau menjadi perusahaan publik.
Sayangnya sebagian besar wirausaha tidak seperti Nadiem dan Zaky, kebanyakan dari mereka memulai usahanya karena tersingkirkan dari pasar tenaga kerja formal. Fenomena ini disebut juga oleh Thurik (2007) sebagai ‘efek pelarian’ (refugee effect). Membuka usaha, terutama di sektor informal, merupakan sebuah bentuk ‘pelarian’ dari kondisi menganggur karena tidak ada pilihan lain untuk bekerja. Jangankan menopang pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru, sebagian besar usaha mikro kecil ini cenderung stagnan dan tidak menghasilkan keuntungan signifikan.
Sama halnya dengan Mang Asep, penjual bubur di dekat rumah penulis yang sejak dulu sampai sekarang masih bertahan dengan gerobak bututnya. Pertanyaannya, apakah kebanyakan wirausaha ini harus kita paksa untuk terus tumbuh?
Masalah data dan definisi wirausaha
Berapa jumlah wirausaha di Indonesia saat ini? Jawabannya tergantung bagaimana kita mendefinisikan wirausaha. Jika wirausaha adalah semua orang yang membuka usaha, baik itu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, tentu angka pengusaha di Indonesia sangat fantastis. Di tahun 2018, Kementerian UMKM melansir bahwa jumlah usaha mikro saja lebih dari 64 juta unit usaha.
Sementara itu, survei tenaga kerja Indonesia (Sakernas) yang dirilis Badan Pusat Statistik membedakan tiga jenis tenaga kerja yang melakukan usaha: (1) mereka yang berusaha sendiri, (2) mereka yang berusaha dibantu buruh tidak dibayar, dan (3) mereka yang berusaha dibantu buruh yang dibayar. Di tahun 2019, jumlah pelaku usaha yang dibantu oleh buruh yang dibayar hanyalah sebanyak 4,3 juta orang, atau sebesar 3,3 persen dari angkatan kerja Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah total populasi, rasionya hanya sebesar 1,6 persen. Rasio tersebut terbilang stagnan sejak tahun 2012, artinya peningkatan jumlah wirausaha di sektor formal selama delapan tahun terakhir besarnya tidak signifikan. Sementara jika mengikutsertakan tenaga kerja yang berusaha sendiri dan yang berusaha dibantu oleh buruh tidak dibayar, jumlah wirausaha Indonesia mencapai 48 juta orang, atau 36 persen dari angkatan kerja. Sejak tahun 2012, jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri meningkat sebesar 26 persen, lebih besar dari pertumbuhan jumlah karyawan/pegawai yang hanya sebesar 20 persen. Hanya saja, angka ini menjadi tidak relevan karena mengikutsertakan pedagang kaki lima, usaha warung, dan pekerja gig (pekerja tidak tetap berdasarkan proyek atau dengan jangka waktu tertentu) seperti sopir ojek daring atau pekerja lepas (freelance) di sektor jasa. Tentu bukan jenis wirausaha seperti ini yang kita harapkan dapat menopang ekonomi nasional selama dua puluh tahun ke depan yang kemudian diharapkan membuat kita naik kelas menjadi negara maju.
Bukan tentang kuantitas
Para pejabat publik sering terjebak menjadikan angka atau rasio tertentu dalam menentukan jumlah wirausaha ideal sebagai indikator kemajuan. Angka ini dijadikan ukuran kesuksesan dan kemudian diterjemahkan ke dalam turunan kebijakan kewirausahaan dalam bentuk pelatihan, pinjaman modal, dan program-program lainnya. Inilah yang menjadi sesat pikir dari kebijakan kewirausahaan.
Dalam bukunya “Poor Economics”, peraih nobel ekonomi Banerjee dan Duflo mengungkapkan masalah utama mengapa kebanyakan wirausaha mikro kecil cenderung stagnan: wirausaha adalah aktivitas yang sulit. Tidak semua orang punya akses dan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya. Artinya, wirausaha bukanlah untuk semua orang. Maka, menjadi ironi apabila pemerintah justru berorientasi untuk menciptakan wirausaha sebanyak-banyaknya.
Global Entrepreneurship Monitor (2009) justru menyimpulkan bahwa seharusnya semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, semakin sedikit jumlah wirausaha yang membuka bisnis baru. Hal ini sejalan dengan prinsip skala ekonomi. Seiring membesarnya pasar dan permintaan, seharusnya semakin banyak tenaga kerja yang dapat terserap menjadi karyawan di perusahaan besar yang lebih efisien. Maka, dengan sendirinya usaha mikro dan kecil akan berkurang karena manfaat menjadi pegawai di perusahaan besar akan melebihi manfaat membuka usaha sendiri.
Memang tidak dapat disangkal, saat ini usaha mikro dan kecil berkontribusi besar bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia (94 persen). Namun, nilai ini tidak sebanding dengan produktivitas ekonomi dari usaha menengah dan besar. Sebagai contoh, usaha mikro dan kecil hanya menopang 61 persen PDB Indonesia, hanya menyerap 30 persen investasi, dan hanya menghasilkan 4 persen ekspor. Dengan fakta ini, tentu kita ingin lebih banyak lagi menghadirkan wirausaha level menengah atau besar, bukan yang stagnan di level mikro atau kecil.
Prioritas kebijakan
Implikasinya, yang harus dilakukan ke depan bukanlah memaksakan program kewirausahaan semata-mata untuk menambah jumlah wirausaha baru atau mendorong seluruh usaha yang ada agar bisa naik kelas. Justru usaha mikro dan kecil yang tidak produktif harus dikurangi dengan memperkuat sektor formal dan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki pilihan lain untuk bekerja. Maka dari itu, perlu ada sasaran prioritas bagi kebijakan kewirausahaan.
Sejak awal, sasaran kebijakan haruslah diperuntukkan bagi mereka yang punya potensi untuk tumbuh dan berkembang. Ukuran kesuksesan program perlu diubah menjadi pertumbuhan bisnis dan produktivitas, bukan lagi sekadar kuantitas wirausaha baru yang dihasilkan, apalagi sekadar yang lulus mengikuti program. Dengan begitu, sumber daya program yang terbatas akan bisa dialokasikan dengan optimal.
Pertanyaan selanjutnya, siapakah sasaran ideal kebijakan kewirausahaan agar program yang disusun berjalan lebih efektif dan menghasilkan dampak luas? Pertama, kebijakan kewirausahaan harus diprioritaskan kepada sektor tertentu yang menghasilkan eksternalitas positif bagi ekonomi lokal dan nasional. Di antaranya adalah wirausaha di sektor manufaktur dan sektor jasa modern (tradable service) seperti sektor digital atau keuangan yang layanannya tidak perlu dimediasi oleh kedekatan jarak. Wirausaha di sektor-sektor ini secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor lain dan bahkan berpotensi menurunkan kemiskinan (Lee dan Rodriguez-Pose, 2020). Sebagai ilustrasi, Moretti (2010) menghitung bahwa efek pengali sektor manufaktur di Amerika Serikat adalah sebesar dua kali lipat. Artinya, dibukanya sebuah pabrik baru yang menyerap 100 orang karyawan dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal dengan menciptakan 200 pekerjaan baru lainnya, misalnya pekerjaan di sektor jasa akomodasi, penyedia makanan minuman, atau jasa lokal lainnya yang beraglomerasi di sekitar pabrik tersebut yang muncul akibat meningkatnya konsumsi masyarakat.
Kedua, sasaran kebijakan harus berfokus kepada wirausaha lulusan universitas karena kelompok ini terbukti memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan menghasilkan eksternalitas positif. Hal ini berkaitan dengan konsep modal manusia (human capital) dimana pendidikan tinggi berperan meningkatkan keterampilan dan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan usahanya. Namun, tidak semua wirausaha berbasis kampus perlu menjadi prioritas kebijakan. Lulusan universitas yang perlu didukung oleh kebijakan sebaiknya bukan mereka yang berbisnis di sektor jasa lokal seperti restoran yang justru bersaing dengan usaha mikro kecil pada umumnya sehingga membuat pasar lokal menjadi jenuh. Bisnis yang didukung oleh kebijakan kewirausahaan haruslah bisnis berbasis teknologi sebagai wujud dari hilirisasi riset di universitas (university spinoff).
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan wirausaha mikro kecil yang merupakan mayoritas pelaku usaha kita. Namun, makna wirausaha sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia perlu kita pertanyakan kembali dan tidak disikapi secara berlebihan.
Tidak semua wirausaha memiliki dampak yang luas dan berperan bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dibuat prioritas dalam merancang kebijakan kewirausahaan. Dengan berfokus kepada wirausaha yang berpotensi untuk tumbuh, diharapkan akan terjadi efek menetes ke bawah (trickle down effect) yang manfaatnya dirasakan semua pihak. Peningkatan produktivitas dan taraf hidup secara agregat dengan sendirinya akan turut meningkatkan daya beli masyarakat, menyerap tenaga kerja baru, dan menggeliatkan aktivitas usaha mikro kecil lain yang sebenarnya bukan sasaran utama dari kebijakan kewirausahaan tersebut.
***
Keterangan:
- Artikel ini merupakan aset pengetahuan organisasi dengan nomor registrasi DOCTRINE UK No. 2022-11-18-Articles.
- Doctrine UK tidak bertanggung jawab atas pandangan yang diungkapkan dalam tulisan dan pandangan tersebut menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.